WORLD OCEAN CONFERENCE DAN KEADILAN PERIKANAN
World Ocean Conference digelar pada 11-15 Mei 2009 di Manado. Selain itu, akan digelar Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, yang antara lain akan membahas isu-isu konservasi, baik spesies maupun terumbu karang, serta perikanan berkelanjutan. Isu konservasi ini merupakan isu penting mengingat problem sumber daya kelautan yang makin rusak. Bayangkan, kekayaan terumbu karang kita, yang mencapai 18 persen terumbu karang dunia, sebagian sudah rusak. Bahkan hanya 6 persen yang berada dalam kondisi sangat baik. Belum lagi kondisi perikanan, yang sebagian besar sudah melewati ambang batas lestari.
Karena itulah berkembang kawasan-kawasan konservasi yang antara lain berbentuk daerah perlindungan laut, taman nasional laut, dan kawasan konservasi laut daerah, yang sampai 2010 ditargetkan mencapai 10 juta hektare. Yang menjadi persoalan, konservasi sering kali dianggap sebagai penghambat peningkatan kesejahteraan nelayan karena tertutupnya daerah tangkapan nelayan akibat zonasi. Akibatnya, pemerintah daerah dan nelayan sering kali alergi terhadap istilah konservasi. Ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga merupakan masalah dunia. Hampir di semua negara yang sedang berkembang mengalami kasus yang sama. Bagaimana kita menyikapi hal ini?
Dalam perspektif ilmu sosial, konservasi bukanlah sebuah konsep atau metode yang berlaku secara universal. Konservasi yang diterjemahkan dalam bentuk kawasan-kawasan konservasi merupakan hasil konstruksi sosial komunitas akademik di Barat yang kemudian berusaha diterapkan di dunia ketiga. Ini pola konservasi yang positivistik. Sebenarnya setiap masyarakat memiliki konstruksi sendiri atas konservasi, yang sering disebut pola konservasi yang konstruktivistik.
Di Jepang sulit ditemukan istilah konservasi. Yang ada istilah pengelolaan perikanan. Praktek perikanan yang bertanggung jawab tidak lain merupakan cara nelayan Jepang melakukan "konservasi", sehingga di Jepang tidak ada istilah kawasan konservasi. Di Maluku, masyarakat melakukan "konservasi" dengan sasi. Masyarakat lain beda lagi, bergantung pada kebudayaan setempat. Nah, pengakuan terhadap eksistensi keberagaman cara masyarakat memelihara alam adalah yang disebut Flitner (2009) sebagai keadilan pengakuan (justice of recognition). Sebenarnya kini keadilan pengakuan telah diupayakan yang tecermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang mengakui eksistensi hak adat dalam pengelolaan pesisir.
Seiring dengan CTI, di kawasan timur banyak sekali ditemukan cara-cara masyarakat "berkonservasi". Namun, dengan hadirnya CTI dan penetapan Laut Sawu sebagai kawasan konservasi, isu aktual yang berkembang saat ini tidak hanya soal terumbu karang, tapi juga konservasi mamalia paus, mengingat wilayah tersebut merupakan jalur migrasi paus, dan di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, ada masyarakat penangkap paus. Apakah konservasi di wilayah CTI harus melarang mereka menangkap paus?
Perburuan paus melibatkan 10-15 orang dalam satu perahu tanpa mesin. Menurut mereka, kegagalan menangkap paus bukanlah masalah teknis, melainkan masalah etik-sosial. Kegagalan memburu paus merupakan cerminan masalah di darat. Kalau di darat bermasalah, di laut pun akan bermasalah, sehingga kegagalan memburu paus harus diselesaikan dengan menyelesaikan dulu masalah lain di darat, yang, menurut cara berpikir positivistik, tidak ada hubungannya. Jadi orang takut berkonflik karena akan berdampak pada kegagalan berburu paus. Dengan cara itulah sistem sosial relatif stabil, dan paus merupakan pilar untuk stabilitas sosial itu.
Memburu paus sudah menjadi kegiatan turun-temurun dan bahkan sudah menjadi inti kebudayaan (cultural core). Pendekatan ekologi-budaya ala Julian Steward (1955) mungkin bisa menjelaskan bagaimana kebudayaan masyarakat Lamalera terbentuk. Menurut Steward, kebudayaan terbentuk karena pengaruh lingkungan lokal, tapi tidak semua unsur kebudayaan merupakan hasil interaksi dengan alam. Hanya unsur tertentu yang kuat interaksinya dengan alam, yaitu unsur teknologi, pola perilaku, pola permukiman, struktur kekerabatan, organisasi sosial, dan tenurial.
Nah, inti kebudayaan di Lamalera adalah memburu paus, sehingga teknologi yang berkembang, aturan adat, pola perilaku, dan organisasi sosial yang berkembang terkait dengan paus. Bahkan institusi ekonomi yang masih mengandalkan barter pun pada akhirnya merupakan konsekuensi perburuan paus. Ada sistem bagi hasil yang sudah baku, dan dalam sistem tersebut diatur bagaimana bagian anak yatim dan janda. Artinya, memburu paus tidak semata aktivitas ekonomi, tapi juga merupakan pilar mempertahankan sistem sosial di mana keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan. Dengan melihat eratnya hubungan paus dan sistem sosial, tentu tidaklah bijak membuat desain memisahkan masyarakat Lamalera dengan inti kebudayaannya.
Masyarakat Lamalera punya cara sendiri "berkonservasi". Masih digunakannya alat tradisional merupakan cara mereka beradaptasi dengan alam. Meskipun dulu pernah ada introduksi alat pembunuh paus yang lebih modern, toh, mereka menolaknya. Mereka memiliki kearifan untuk membatasi jumlah tangkapan dengan tetap mempertahankan cara tradisionalnya. Meski demikian, keadilan perikanan tidak hanya dalam hal pengakuan. Namun, mesti juga ada apa yang disebut Flitner (2009) sebagai keadilan distributif (distributive justice). Tipe keadilan ini menekankan pentingnya akses nelayan pada pemanfaatan sumber daya. Banyaknya konflik nelayan dengan pengelola kawasan konservasi merupakan akibat terusiknya keadilan distributif mereka.
Karena itu, CTI mesti memperhatikan dua tipe keadilan tersebut. Bila tidak, CTI hanya akan makin mengukuhkan pola konservasi positivistik, yang selama ini justru sering bermasalah. Dan, bila dibiarkan terus, sama saja dengan "menyelesaikan masalah dengan masalah".
Label: back to school





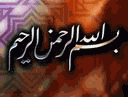














0 komentar:
Posting Komentar